Kematian adalah takdir yang pasti. Namun cara kematian kadang menyisakan luka yang dalam—bukan hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi bagi nurani kita bersama. Ketika seorang kepala wilayah, pemimpin yang seharusnya dihormati dan diajak berdialog, justru harus meregang nyawa di tangan warganya sendiri, kita patut bertanya: Di mana hati nurani kita?
Apakah satu persoalan kecil—seberat apapun rasanya di dada—layak dibayar dengan nyawa seseorang? Kebrutalan yang muncul dari amarah sesaat telah menghapus satu kehidupan, memutus harapan keluarga, dan mencoreng wajah kemanusiaan kita sendiri. Dalam setiap tikaman yang diberikan, bukan hanya tubuh yang robek, tetapi juga nilai-nilai kebersamaan dan kepercayaan.
Permasalahan dalam hidup pasti akan datang, tetapi tidak satu pun layak diselesaikan dengan kekerasan. Kita lupa, bahwa pemimpin juga manusia—punya keterbatasan, punya tekanan, dan punya niat baik yang mungkin tidak selalu bisa segera diwujudkan. Kita semua terluka saat seorang kepala desa harus mati bukan karena usia, bukan karena sakit, tapi karena kebencian yang tak sempat diredam.
Marilah kita belajar dari tragedi ini. Bahwa ketika lidah tak mampu berkata dengan sabar, tangan jangan sampai bicara dengan kekerasan. Hentikan budaya menyalahkan dan mulai rawat budaya memahami. Karena darah yang tumpah hari ini adalah peringatan bagi kita semua: bila hati tak lagi mampu mengampuni, maka kita perlahan kehilangan sisi kemanusiaan.
Semoga kejadian ini menjadi cermin. Bukan hanya untuk mengenang yang telah pergi, tetapi untuk memperbaiki cara kita hidup bersama sebagai sesama manusia.






































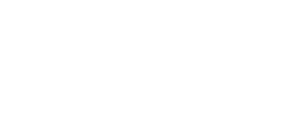
Desago
11 Agustus 2025 00:43:11
Salut untuk Desa Bobawa yang meluncurkan website berbasis Opensid, wujud nyata transparansi dan kemajuan...